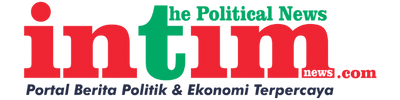Menikmati Makassar di Awal Tahun: Pantai Losari, Hujan, dan Ritme Kota

“A city is not a concrete jungle, it is a human zoo.” – Desmond Morris
MAKASSAR – Makassar bukan kota yang asing. Terakhir kali saya singgahi pada akhir 2022, dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional LAPMI HMI se-Indonesia, dulu kota ini hadir dalam ritme yang padat dan formal. Ruang pertemuan, jadwal kegiatan, dan waktu yang terbatas menjadikan Makassar lebih banyak berfungsi sebagai latar.
Kunjungan kali ini berlangsung dengan tempo yang berbeda, bertepatan dengan awal tahun, ketika perjalanan memberi ruang untuk melihat kota dengan lebih perlahan.
Perjalanan dimulai dari Palangka Raya pada Selasa sore, 6 Januari 2026, transit di Surabaya, dan berakhir di Makassar pada Selasa malam. Bandara Sultan Hasanuddin menyambut dengan udara hangat dan aktivitas kota yang masih terasa meski hari telah larut.
Menginap di Aerotel Smile, kawasan Pantai Losari, menghadirkan sudut pandang yang lain. Kamar di lantai 11 menghadap langsung ke laut, memungkinkan menyaksikan matahari terbit dan tenggelam dari satu tempat yang sama. Pagi terasa tenang, sore berwarna jingga, sementara malam Losari tetap hidup oleh cahaya lampu dan lalu lintas yang tak pernah sepenuhnya berhenti.
Hari pertama diisi dengan menyusuri kawasan Masjid 99 Kubah dan Center Point of Indonesia (CPI). Masjid dengan kubah berwarna-warni berdiri mencolok di tepi laut, menjadi simbol wajah baru Makassar yang memadukan nilai religius dan estetika modern. Sementara CPI berkembang sebagai ruang publik, tempat warga berkumpul, berjalan santai, dan menikmati kawasan pesisir kota.
Untuk mobilitas, sepeda motor menjadi pilihan. Keputusan ini menghadirkan pengalaman yang sering diceritakan banyak orang: kemacetan Makassar. Jalanan padat, kendaraan bergerak rapat, klakson bersahutan dalam irama yang tampak semrawut, namun tetap mengalir. Di situ, Makassar terasa hidup, cepat, dan menuntut kewaspadaan.
Interaksi dengan warga lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan. Percakapan singkat hampir selalu diwarnai logat khas: iye, ji, mi, ki. Bahasa yang awalnya terasa asing, perlahan terdengar akrab. Tutur yang lugas dan apa adanya menghadirkan kesan hangat tanpa berlebihan.

Hari berikutnya, wajah Makassar berubah. Hujan turun sejak pagi hingga sore, memperlambat ritme kota. Dalam suasana seperti itu, Benteng Rotterdam terasa lebih sunyi dan reflektif. Dinding tua dan bangunan kolonialnya menghadirkan lapisan sejarah yang kontras dengan kawasan modern di sekitarnya, seolah mengajak untuk sejenak berhenti dan melihat perjalanan panjang kota ini.
Menjelang akhir perjalanan, kunjungan ke toko oleh-oleh menjadi penutup. Percakapan ringan kembali memperlihatkan keramahan yang sama: bahasa boleh berbeda, tetapi rasa diterima tetap terasa.
Makassar meninggalkan kesan sebagai kota yang mudah melekat. Bukan hanya karena lautnya, ikon-ikonnya, atau kemacetannya, tetapi karena irama kehidupan yang terus bergerak dan logat yang perlahan akrab di telinga.
Dalam konteks itulah kutipan Desmond Morris menemukan maknanya. Makassar bukan hutan beton yang kaku, melainkan ruang tempat manusia berinteraksi, beradaptasi, dan saling membaca satu sama lain.
Dari Pantai Losari hingga jalanan yang padat, dari logat lokal hingga hujan yang turun seharian, Makassar hadir sebagai kota yang hidup oleh manusianya, dan karena itu, selalu layak untuk diamati dan dicatat.
Debar di Makassar meski sebentar memberi ruang untuk memulai tahun dengan langkah yang lebih jernih.
Sebuah tulisan reflektif dari Andrian Fatkhurrohman Sidiq (Editor Intimnews)